Dalam tradisi keilmuan Islam, istilah sedekah jariyah kerap disempitkan maknanya hanya pada praktik wakaf. Hal ini berakar dari dominasi pandangan mayoritas ulama yang menafsirkan sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir pascawafat sebagai merujuk khusus pada wakaf. Namun, pendekatan ini menyisakan pertanyaan epistemologis: apakah pembatasan tersebut benar-benar mencerminkan cakupan makna yang dimaksud oleh Rasulullah saw.?
Pertanyaan epistemologis dalam konteks ini, adalah “bagaimana kita tahu bahwa itu benar?”, “dari mana sumber pengetahuan itu berasal?”, dan “apakah cara kita memahami sesuatu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau metodologis?”
Melalui pendekatan fiqhiyyah dan analisis linguistik, tulisan ini berusaha memahami bahwa pahala yang terus mengalir bukanlah monopoli satu bentuk amal, melainkan hasil dari setiap kontribusi yang berdampak berkelanjutan. Dengan demikian, pemaknaan sedekah jariyah perlu dibuka kembali ruangnya agar mencerminkan keluasan syariat dan semangat keberlanjutan amal dalam Islam.
1. Definisi Sedekah
- Etimologi (Linguistik)
Al-Raghib al-Asfahani menerangkan,
وَالصَّدَقَةُ مَا يُخْرِجُهُ الإِنْسَانُ مِنْ مَالِهِ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ كَالزَّكَاةِ، لَكِنِ الصَّدَقَةُ فِي الأَصْلِ تُقَالُ لِلْمُتَطَوَّعِ بِهِ، وَالزَّكَاةُ لِلْوَاجِبِ، وَقَدْ يُسَمَّى الْوَاجِبُ صَدَقَةً إِذَا تَحَرَّى صَاحِبُهَا الصِّدْقَ فِي فِعْلِهِ (المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهانى أٍ [ت 502 هـ ]، ص480)
Sedekah adalah sesuatu yang dikeluarkan seseorang dari hartanya dalam rangka mendekatkan diri (kepada Allah), seperti zakat. Namun, pada asalnya, kata sedekah diungakpkan untuk sesuatu yang bersifat sukarela, sedangkan kata zakat untuk yang wajib. Kadang-kadang, sesuatu yang wajib pun bisa disebut sebagai sedekah apabila pelakunya benar-benar mengupayakan keikhlasan dalam amalnya.
Secara bahasa, pemberian dengan niat pendekatan diri kepada Allah Swt. adalah sedekah, baik pemberian tersebut bersifat wajib, maupun tidak tidak wajib (sukarela/tathawwu’). Fokus makna sedekah secara etimologi adalah “niat pendekatan diri kepada Allah Swt.”
- Terminologi (Ishthilahi)
Al-Nawawi menerangkan,
اعْلَمْ أَنَّ حَقِيقَةَ الصَّدَقَةِ إعْطَاءُ الْمَالِ وَنَحْوِهِ بِقَصْدِ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ (المجموع شرح المهذب, النوويّ [ت 676 هـ ]، ج 6، ص 246، ط المنيرية)
Ketahuilah bawa pada hakikat sedekah adalah pemberian harta dan sejenisnya—tanpa imbalan—dengan niat mengharap pahala akhirat. (Meski begitu) kadang-kadang diungkapkan untuk selain itu.
Sama dengan definisi etimologinya, definisi terminologi ini mencakup sedekah sukarela (tathawwu’) dan sedekah wajib (fardh) yaitu zakat. Namun, dalam tradisi fuqaha`, ketika kata sedekah disebut secara mutlak (tanpa keterangan), maka yang dimaksud adalah sedekah sukarela. Yang terakhir ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Syirbiniy,
َصْلٌ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ، وَهِيَ الْمُرَادَةُ عِنْدَ الْإِطْلَاق غَالِبًا (مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني [ت 977 هـ]، ج 4، ص 194، دار الكتب العلمية)
2. Penerima Sedekah
Para ahli fikih tidak berbeda pendapat mengenai kebolehan memberikan sedekah sukarela kepada orang yang tidak membutuhkan (orang kaya), meski perbuatan itu tidak sesuai dengan yang lebih utama (khilaf al-awla). Hanya saja, pemberian ini tidak dianggap sebagai sedekah kecuali jika dimaksudkan untuk mencari pahala akhirat.
Imam Al-Nawawi menyatakan,
تَحِلُّ صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ لِلْأَغْنِيَاءِ بِلَا خِلَافٍ فَيَجُوزُ دَفْعُهَا إلَيْهِمْ وَيُثَابُ دَافِعُهَا عَلَيْهَا وَلَكِنَّ الْمُحْتَاجَ أَفْضَلُ (المجموع شرح المهذب, النوويّ، ج 6، ص 239، ط المنيرية)
Sedekah sukarela adalah halal (boleh) diberikan kepada orang-orang kaya tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dengan begitu, boleh memberikannya kepada mereka (yang mampu) dan pemberinya akan mendapat pahala atasnya, akan tetapi (memberikannya kepada) orang yang membutuhkan adalah lebih utama.
3. Cakupan Makna Sedekah
Istilah sedekah juga digunakan secara majas (metafora) untuk menyebut seluruh perbuatan baik, sebagaimana dalam sabda Rasulullah saw.
كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ وَمُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ حُذَيْفَةَ)
“Setiap kebaikan adalah sedekah.”
Dalam konteks ini, imam al-Nawawi menyinggung bahwa sedekah bisa berarti bukan berupa pemberian harta, sebagaimana telah disinggung di atas, ,
Ketahuilah bahwa hakikat sedekah adalah memberikan harta dan sejenisnya dengan niat mengharap pahala akhirat, (meski demikian) terkadang ia diungkapkan untuk selain itu.
4. Klasifikasi Sedekah Sukarela
Sedekah sukarela terbagi dalam 2 (dua) kelas:
- Sedekah yang tidak berkelanjutan (munqadhiyah/منقضية):
Sedekah yang tidak berkelanjutan adalah bentuk pengalihan kepemilikan atas barang dan manfaatnya dari pemberi kepada penerima sedekah, atau pemberian izin pemanfaatan barang dari pemberi sedekah kepada penerima sedekah dalam atau hingga waktu tertentu, atau hingga terjadinya suatu peristiwa yang telah ditentukan, di mana pada saat itu sedekah tersebut berakhir.
- Sedekah Berkelanjutan (Jariyah/جارية)
Sedekah Berkelanjutan adalah sedekah yang pahalanya terus mengalir untuk pelakunya sepanjang hidupnya dan setelah kematiannya. Hal ini terjadi dengan cara menahan pokok harta dan melarang adanya tasharruf (pengelolaan yang bersifat memindahkan kepemilikan) pada pokok harta seperti menjualnya, menghibahkannya, dan sejenisnya, sambil memperbolehkan pengambilan manfaatnya. Atau, dengan menyerahkan kepemilikan hasil dari pokok harta kepada penerima sedekah—baik perorangan maupun lembaga—selama aset itu masih ada, setelah terlebih dahulu digunakan untuk pemeliharaan dan perbaikan yang dapat membuatnya berkembang dan hasilnya tidak terputus. Baik sedekah ini dimulai pada masa hidup pemberi sedekah (seperti Wakaf), maupun setelah kematiannya (seperti Wasiat Manfaat yang bersifat abadi).
5. Dasar Hukum Sedekah Jariyah
Dasar legalitas sedekah jariyah adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a.:
أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا). قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ: أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ ابنِ عَمَرَ)
Sesungguhnya Umar bin Khattab mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu beliau mendatangi Nabi saw. untuk meminta petunjuk. Beliau berkata, “Wahai Rasulullah, aku telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah aku mendapatkan harta yang lebih berharga bagiku daripada itu. Apa yang engkau perintahkan terkait dengannya?”
Nabi saw. bersabda, “Jika engkau mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah (hasil)nya.”
Ibnu Umar berkata, “Lalu Umar menyedekahkannya, dengan ketentuan “tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan”. Beliau menyedekahkannya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk membebaskan budak, (pembiayaan kepentingan) di jalan Allah, untuk musafir, dan tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengelolanya untuk memakan darinya dengan cara yang baik, dan memberi makan (orang lain) tanpa bermaksud menumpuk harta.
Di samping itu, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah saw. bersabda,
ِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ
Ketika manusia meninggal dunia, maka (pahala) amalnya terputus darinya kecuali dari tiga hal: dari sedekah jariyah, atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak saleh yang mendoakannya.
6. Tafsir Sedekah Jariyah
Mengomentari hadis yang disebut barusan di atas, al-‘Izz bin ‘Abd al-Salam mengatakan,
الصَّدَقَةُ الْجَارِيَةُ تُحْمَلُ عَلَى الْوَقْفِ وَعَلَى الْوَصِيَّةِ بِمَنَافِعِ دَارِهِ وَثِمَارِ بُسْتَانِهِ عَلَى الدَّوَامِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ كَسْبِهِ، لِتَسَبُّبِهِ إلَيْهِ، فَكَانَ لَهُ أَجْرُ التَّسَبُّبِ (قواعد الأحكام في مصالح الأنام، عبد العزيز بن عبد السلام [ت 660 هـ]، ج 1، ص 135، مكتبة الكليات الأزهرية)
Sedekah jariyah dimaknai sebagai wakaf dan juga sebagai wasiat atas manfaat rumahnya dan hasil kebunnya secara abadi. Karena hal itu merupakan bagian dari usahanya, sebab ia menjadi penyebab terjadinya manfaat tersebut, maka ia mendapatkan pahala atas sebab yang ia lakukan.
7. Definisi Istilah Wakaf dan Wasiat Manfaat
- Definisi Wakaf
(أي الوقْفُ) شَرْعًا حبسُ مَال يُمكن الأنتفاع بِهِ مَعَ بَقَاء عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّف فِي رَقَبَتِه على مَصْرَفٍ مُبَاح (غاية البيان شرح زبد ابن رسلان، شهاب الدين الرملي [ت 1004 هـ]، ص 230، دار المعرفة)
Wakaf, secara istilah, adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan substansi pokoknya, dengan cara memutus hak pengelolaan atas pokok harta tersebut, untuk disalurkan pada tujuan penyaluran yang dibolehkan (secara syariat).
- Definisi Wasiat (Barang atau Manfaat)
(الْوَصِيَّةُ تَمْلِيكٌ مُضَافٌ إلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ) يَعْنِي بِطَرِيقِ التَّبَرُّعِ سَوَاءٌ كَانَ عَيْنًا أَوْ مَنْفَعَةً (تبيين الحقائق، شهاب الدين الشِّلْبِيّ الحنفيّ [ت 1021 هـ]، ج 6، ص 182، المطبعة الكبرى الأميرية)
Wasiat adalah pengalihan kepemilikan yang ditangguhkan hingga setelah kematian dengan cara sukarela (tabarru’); baik itu pada bendanya maupun pada manfaatnya saja.
Contoh pada bendanya: “Saya wasiatkan rumah ini untukmu”. Sedangkan contoh manfaatnya saja: “Saya wasiatkan manfaat rumah ini untukmu”. Dalam 2 (dua) contoh ini, penerima wasiat baru berhak memiliki benda atau manfaatnya setelah pemberi wasiat wafat.
8. Perbedaan Wakaf dan Wasiat Manfaat
Setidaknya, terdapat 6 (enam) perbedaan antara Wakaf dan Wasiat (secara umum), yaitu,
| No. | Sudut Perbedaan | Wakaf | Wasiat |
| 1 | Hakikat hukum dan definisi akad | Menahan pokok harta dan membebaskan manfaatnya untuk digunakan | Pemberian kepemilikan yang berlaku setelah kematian sebagai bentuk hibah, baik benda maupun manfaat |
| 2 | Kekuatan hukum dan kemungkinan pembatalan | Bersifat mengikat dan tidak boleh ditarik kembali menurut mayoritas ulama | Mengikat, tetapi pewasiat boleh menarik kembali seluruh atau sebagian wasiatnya |
| 3 | Status kepemilikan objek hukum | Mengeluarkan benda wakaf dari kepemilikan dan mengkhususkan manfaatnya bagi penerima wakaf | Mencakup pemberian kepemilikan benda atau manfaatnya kepada penerima wasiat |
| 4 | Waktu Mula berlakunya akibat hukum | Efek hukum pemberian manfaat berlaku sejak hidup wakif dan berlanjut setelah wafat | Efek hukum pemberian baru berlaku setelah pewasiat wafat |
| 5 | Batasan kuantitatif pemberian | Tidak ada batas maksimal harta yang boleh diwakafkan | Tidak boleh melebihi sepertiga harta kecuali dengan izin ahli waris |
| 6 | Keterlibatan ahli waris | Boleh diberikan kepada ahli waris kecuali jika dilakukan saat sakit menjelang kematian | Tidak sah jika diberikan kepada ahli waris kecuali dengan izin ahli waris lainnya |
9. Hubungan Sedekah Jariyah dan Wakaf Menurut Mayoritas
Jumhur (mayoritas) ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariyah dalam hadis sebelumnya adalah wakaf, bukan bentuk perbuatan kebaikan lainnya meskipun dari sudut frasanya yang general, hadis tersebut mencakup yang terakhir ini. Ini dianggap sebagai bentuk “frasa umum (tetapi) yang diinginkan adalah makna khusus” (‘amm yuradu bihi al-khashsh). Dengan begitu, mereka memaknai sedekah jariyah (dalam hadis) sebagai wakaf, dan mengesampingkan wasiat manfaat karena praktiknya yang jarang terjadi.
Al-Khathib al-Syirbini menulis,
وَالصَّدَقَةُ الْجَارِيَةُ مَحْمُولَةٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ عَلَى الْوَقْفِ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فَإِنَّ غَيْرَهُ مِنْ الصَّدَقَاتِ لَيْسَتْ جَارِيَةً، بَلْ يَمْلِكُ الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ أَعْيَانَهَا وَمَنَافِعَهَا نَاجِزًا. وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ بِالْمَنَافِعِ وَإِنْ شَمِلَهَا الْحَدِيثُ فَهِيَ نَادِرَةٌ، فَحَمْلُ الصَّدَقَةِ فِي الْحَدِيثِ عَلَى الْوَقْفِ أَوْلَى (مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني [ت 977 هـ]، ج 3، ص 523، دار الكتب العلمية)
(Frasa) sedekah jariyah (dalam hadis) menurut para ulama dimaknai sebagai wakaf, sebagaimana dikatakan oleh al-Rafi’i, karena bentuk sedekah selain itu tidak bersifat ‘mengalir’, melainkan penerima sedekah langsung memiliki barang dan manfaatnya secara tuntas (najiz). Adapun wasiat manfaat, meskipun tercakup dalam hadis, ia jarang terjadi. Maka, memaknai sedekah dalam hadis sebagai wakaf adalah lebih utama.
Maksud “najiz” dalam konteks ini adalah:
- Sedekah biasa: Memberikan kepemilikan penuh atas benda dan manfaatnya kepada penerima, secara langsung dan final (tamlik najiz).
- Berbeda dengan wakaf: Dalam wakaf, benda tidak dimiliki oleh penerima, hanya manfaatnya yang dialirkan, dan itu pun dengan syarat tertentu.
- Implikasi hukum: Sedekah yang sifatnya najiz tidak memiliki kesinambungan pahala seperti wakaf, karena manfaatnya bisa habis atau berpindah tangan.
Dalam istilah hukum Islam, “tamlik najiz” (تَمْلِيكٌ نَاجِزٌ) sering digunakan untuk membedakan antara pemberian yang langsung efektif (seperti hibah atau sedekah biasa) dan pemberian yang tertunda atau bersyarat (seperti wasiat atau wakaf).
10. Makna Sedekah Jariyah dalam Pandangan Ulama Syafi’iyyah Muta`akhkhirun
Akan tetapi, para ulama muta`akhkhirun dari kalangan Syafi’iyyah tidak menerima pandangan mayoritas ini secara mutlak, melainkan menjadikannya bahan kajian dan tidak memutuskan secara pasti bahwa selain wakaf tidak termasuk dalam pengertian sedekah jariyah yang disebut dalam hadis. Mereka bersandar pada hadis-hadis lain, di antaranya:
- Riwayat Ibnu Majah dalam Sunan-nya dari Abu Hurairah r.a.,
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، أَوْ مُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْحِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، تَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ
Sesungguhnya di antara amal dan kebaikan seorang mukmin yang akan menyusulnya setelah ia wafat adalah (1) ilmu yang ia ajarkan dan sebarkan, (2) anak saleh yang ia tinggalkan, (3) mush-haf yang ia wariskan, (4) masjid yang ia bangun, (5) rumah untuk musafir yang ia bangun, (6) sungai yang ia alirkan, atau (7) sedekah yang ia keluarkan dari hartanya di waktu sehat dan hidupnya, yang akan menyusulnya setelah ia wafat.
- Riwayat al-Bazzar Musnad-nya dari Anas r.a.,
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سَبْعٌ يَجْرِي لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا، أَوْ أَجْرَى نَهْرًا، أوْ حَفَرَ بِئْرًا، أوْ غَرَسَ نَخْلًا، أَوْ بَنَى مَسْجِدًا، أَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا، أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ.
Rasulullah saw. bersabda, “Ada tujuh amal yang pahalanya terus mengalir bagi seorang hamba meskipun ia telah berada di dalam kuburnya setelah wafat: (1) orang yang mengajarkan ilmu, (2) orang yang mengalirkan sungai, (3) orang yang menggali sumur, (4) orang yang menanam pohon kurma, (5) orang yang membangun masjid, (6) orang yang mewariskan mussh-haf, (7) atau orang yang meninggalkan anak yang senantiasa memohon ampun untuknya setelah ia wafat.”
Mengomentar hadis riwayat al-Bazzar di atas, al-Hafizh al-Munawi berkata,
(أَوْ غَرَسَ نَخْلًا): أَيْ لِنَحْوِ تَصَدُّقٍ بِثَمَرِهِ بِوَقْفٍ أَوْ غَيْرِهِ. … قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا يُخَالِفُ الْحَدِيثَ الصَّحِيحَ (إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ)، فَقَدْ قِيلَ فِيهِ: (إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ)، وَهِيَ تَجْمَعُ مَا ذُكِرَ مِنَ الزِّيَادَةِ. (فيض القدير، المناوي القاهري [ت 1031 هـ]، ج 4، ص 87، المكتبة التجارية الكبرى)
(… Menanam pohon kurma) maksudnya adalah untuk tujuan seperti menyedekahkan buahnya, baik melalui wakaf atau selainnya… Al-Baihaqi berkata, “Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis sahih “Jika anak Adam wafat, terputus amalnya kecuali dari tiga hal …”, karena di dalamnya disebutkan: ‘kecuali dari sedekah jariyah’, dan (sedekah jariyah) ini mencakup praktik-praktik lain yang disebutkan (dalam hadis-hadis lain).
Dengan pernyataan ini, al-Munawi ingin menyampaikan bahwa menanam pohon kurma untuk disedekahkan buahnya (saja) dengan cara selain wakaf juga masuk dalam kategori sedekah jariyah.
Syaikh al-Bujayrimi mempertanyakan mengapa makna sedekah jariyah dipersempit hanya untuk wakaf. Beliau menulis,
انْظُرْ مَا وَجْهُ التَّخْصِيصِ بِالْوَقْفِ مَعَ أَنَّ الصَّدَقَةَ الْجَارِيَةَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ (تحفة الحبيب على شرح الخطيب، البُجَيْرِمِيّ الشافعيّ [ت 1221 هـ]، ج 3، ص 243، دار الفكر)
Perhatikanlah, apa alasan pengkhususan makna sedekah jariyah hanya pada wakaf, padahal sedekah jariyah itu lebih umum daripada itu?
Pertanyaan senada dikemukakan oleh syaikh al-Jamal,
وَلْيُنْظَرْ مَا الْمَانِعُ مِنْ حَمْلِ الصَّدَقَةِ الْجَارِيَةِ عَلَى بَقِيَّةِ الْخِصَالِ الْعَشْرِ الَّتِي ذَكَرُوا أَنَّهَا لَا تَنْقَطِعُ بِمَوْتِ ابْنِ آدَمَ (حاشية الجمل على شرح المنهج، سليمان بن عمر الأزهري، المعروف بالجمل [ت 1204 هـ]، ج 3، ص 576، دار الفكر)
Apa yang menghalangi untuk memaknai sedekah jariyah sebagai seluruh sepuluh amal lainnya yang mereka jelaskan bahwa pahalanya tidak terputus dengan wafatnya anak Adam?
Di samping itu, terdapat al-‘Izz bin ‘Abd al-Salam yang pernyataannya telah dikemukakan di atas bahwa,
“Sedekah jariyah dimaknai sebagai wakaf dan juga sebagai wasiat atas manfaat rumahnya dan hasil kebunnya secara abadi.”
Berdasarkan keterangan barusan,
- Al-Bujayrimi dan al-Jamal membuka ruang tafsir bahwa sedekah jariyah tidak terbatas pada wakaf, meskipun wakaf lebih dominan dalam praktik.
- Al-‘Izz bin ‘Abd al-Salam secara eksplisit menyatakan bahwa wasiat manfaat yang berkelanjutan juga termasuk sedekah jariyah, karena ia merupakan hasil usaha dan sebab yang ditanamkan oleh pelakunya.
11. Analisis Akhir
Sampai sini, tidak berlebihan jika ditegaskan bahwa konsep sedekah jariyah lebih umum daripada sekedar konsep wakaf; karena konsep wasiat manfaat juga dapat disebut sebagai sedekah jariyah, meski konsepnya berbeda dari wakaf. Pengkhususan makna sedekah jariyah dalam hadis oleh mayoritas ulama hanya pada wakaf, tidak berarti bahwa sedekah selain wakaf secara mutlak tidak termasuk dalam keumuman frasa sedekah jariyah. Persoalan mereka adalah: apakah lafal umum dalam hadis ini dimaksudkan untuk makna umum, atau dimaksudkan untuk makna khusus? Mereka lebih memilih: dimaksudkan untuk makna khusus.
Penafsiran ini yang dipermasalahkan oleh para ulama muta’akhkhirun. Menurut mereka, zhahir-nya, yang menjadi pegangan seharusnya keumuman lafal, apalagi tidak ada penghalang untuk membiarkan frasa tersebut tetap dalam makna generalnya; karena itulah yang menjadi prinsip dasar (bahwa lafal umum dibiarkan dengan keumumannya sampai terbukti ada takhshish), ditambah adanya bukti-bukti (qarinah) untuk mempertahankan prinsip ini. Dengan cara pikir ini, wasiat manfaat juga termasuk yang dimaksud oleh lafal/frasa “sedekah jariyah” dalam hadis. Apalagi telah disepakati oleh para ulama bahwa wasiat manfaat adalah sedekah, dan pahalanya mengalir untuk pelakunya sebagaimana mengalirnya pahala wakaf. Meskipun diakui bahwa wakaf lebih utama dari sisi bahwa pahalanya dimulai semasa hidup orang yang bersedekah dan berlanjut setelah kematiannya, berbanding pahala wasiat manfaat yang baru dimulai setelah kematian.
Artikel ini merupakan parafrasa dari artikel ini (diakses terakhir 16 September 2025, pukul 12:41 WIB)




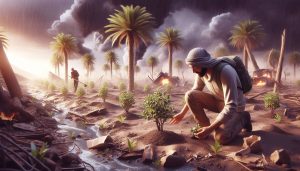
 Situs ini berisi tulisan dan informasi yang berasal dari sumber internal DSN sebagai lembaga, pengurus DSN-MUI, maupun sumber eksternal di luar DSN-MUI. Setiap pandangan atau opini penulis, baik dari pengurus DSN MUI atau pihak eksternal adalah pendapat dan ekspresi pribadi penulisnya. DSN-MUI sebagai lembaga tidak bertanggungjawab atas pandangan dan opini tersebut kecuali dinyatakan sebagai pendapat DSN-MUI sebagai lembaga.
Situs ini berisi tulisan dan informasi yang berasal dari sumber internal DSN sebagai lembaga, pengurus DSN-MUI, maupun sumber eksternal di luar DSN-MUI. Setiap pandangan atau opini penulis, baik dari pengurus DSN MUI atau pihak eksternal adalah pendapat dan ekspresi pribadi penulisnya. DSN-MUI sebagai lembaga tidak bertanggungjawab atas pandangan dan opini tersebut kecuali dinyatakan sebagai pendapat DSN-MUI sebagai lembaga.